Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan
Amich Alhumami
“I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development.”
Lee Kwan Yew—Mantan PM Singapura
Kaitan demokrasi-kesejahteraan sudah sejak lama menjadi perdebatan panjang di kalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi. Perdebatan berpangkal pada pertanyaan kembar: Apakah demokrasi dapat mengantar ke kesejahteraan? Apakah demokrasi merupakan jalan tunggal menuju kemakmuran?
Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif-hipotetikal karena bergantung pada sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier- kausalistik, melainkan nonlinier- kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik.
Jika prasyarat fundamental tidak terpenuhi, demokrasi akan menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan bisa berubah menjadi katastrofi sosial. Inilah yang sekarang dialami negara-negara yang berada dalam masa transisi menuju konsolidasi demokrasi (Afrika, Amerika Latin). Berbagai studi menunjukkan, sekitar 80 persen negara-negara sedang berkembang sedang dalam periode transisi untuk memantapkan demokrasi.
Maka, argumen klasik yang diusung SM Lipset (1959) pun kembali bergema, demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga-negara berpendidikan memadai serta kelas menengah kuat dan independen. Keseluruhan argumentasi SM Lipset bertolak dari tesis berikut: “Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin ia yakin dalam nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi.”
Di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, organisasi masyarakat sipil tak berfungsi, maka demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik, yang menawarkan janji-janji populis agar bisa dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau penjabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih mereka hanya peduli dengan kepentingan sendiri (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi), lalu melenggang meninggalkan rakyat berkubang dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kekuasaan dijadikan sebagai “mesin pencetak uang” untuk membeli suara dalam pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung siklikal mengikuti kalender pemilu lima tahunan.
Bukan jalan tunggal
Tingkat kesejahteraan yang tinggi memang banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, Joseph Siegle (2007) dengan lantang meyakinkan dunia, “demokrasi di negara-negara industri dikenal sebagai yang paling dinamis, inovatif, dan ekonomi yang paling produktif di dunia; demokrasi ini telah memungkinkan negara-negara maju mengakumulaasi dan mempertahankan perbaikan kualitas hidup warga negara mereka selama beberapa generasi.”
Selama empat dekade terakhir sejak 1960-an, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara otoriter (lihat juga Halperin, Siegle & Weinstein [eds], The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, 2004). Namun, pengalaman Singapura yang secara spektakuler mampu mencapai kemakmuran ekonomi dengan sistem politik semiotoriter menegaskan, ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Pencapaian ekonomi gemilang Korea Selatan dan Taiwan saat ini juga tak bisa dilepaskan sama sekali dari sistem pemerintahan semiotoriter, sampai kedua negara itu memeluk demokrasi secara penuh.
Vietnam yang de facto menganut sistem pemerintahan otoriter juga mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. China adalah contoh lain, yang bereks- perimen mengadaptasi sistem politik otoriter dengan menyerap sistem ekonomi pasar bebas, seperti dianut negara-negara demokrasi liberal. Eksperimentasi China berbuah pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dunia. Tang & Yung (2006) melakukan penelitian mengenai kaitan demokrasi dan kinerja ekonomi di negara-negara kategori high performance Asian economies (HPAEs), menggunakan time-series technique yang disebut autoregressive distributive lag, juga menemukan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional. Kinerja ekonomi bagus tidak bergantung pada pilihan sistem politik, demokrasi, atau otoriter. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya membawa pengaruh minimal pada penguatan demokrasi. Karena tak menemukan dalil ilmiah untuk menjelaskan pencapaian ekonomi yang memesona ini, para sarjana Barat menggolongkan negara-negara HPAEs tersebut sebagai autocratic exceptions.
Fareed Zakaria (2003) menggunakan istilah liberal autocracy dan illiberal democracy, untuk menggambarkan sistem politik nondemokrasi bisa pula mengantarkan ke pertumbuhan ekonomi tinggi. Sangat jelas, setiap negara mempunyai pengalaman berlainan dalam meraih kemakmuran. Jalan menuju kesejahteraan ternyata tidak tunggal. Tak heran bila muncul banyak mitos mengenai demokrasi-kesejahteraan.
Penumpang gelap
Bagi Indonesia, keyakinan demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan bukan lagi mitos, tetapi seolah menjadi kutukan. Sudah hampir satu dekade Indonesia berpaling dari otoritarianisme, tetapi demokrasi tak membawa perubahan apa-apa. Di antara banyak penyebab kebuntuan jalan adalah demokrasi menyediakan ruang bagi penumpang gelap yang kemudian membajak sistem pemerintahan baru. Mereka adalah elite-elite lama yang menguasai sumber daya politik-ekonomi, kapital, dan jaringan di pusat-pusat pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan.
Tanpa lelah mereka terus bersiasat di partai-partai politik untuk meneguhkan oligarki. Bahkan, sebagian menduduki jabatan penting dan strategis di lembaga politik kenegaraan format baru, sambil berpetuah mengenai demokrasi dan kesejahteraan.
Maka, pernyataan kontroversial Wakil Presiden Jusuf Kalla seyogianya dibaca dalam perspektif berbeda. Jusuf Kalla sekadar menyuarakan perasaan putus asa dalam menghadapi elite-elite politik lama, yang secara canggih memanipulasi demokrasi untuk kepentingan kemakmuran sendiri, bukan kesejahteraan rakyat.
Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology, University of Sussex, United Kingdom
Disalin sesuai naskah sumbernya:
Kompas, Kamis, 27 Desember 2007
Klik di sini untuk membaca naskah aslinya

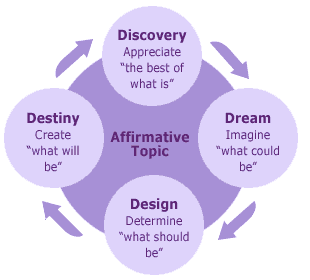

tulisan bagus dan sebuah cerminan kondisi bangsa indonesia saat ini. benar kata mas Amich bahwa hampir satu dekade demokratisasi indonesia hanya mampu mengarahkan sistem politik indonesia, namun efek nyata yang paling nyata adalah lahirnya oligakhi-oligarkhi bak tumor ganas, lebih ganas dari seekor soeharto dulu…
Demokrasi Tidak, Sejahtera Tidak
Salahuddin Wahid
Kembali Wapres Jusuf Kalla melontarkan pernyataan yang memicu komentar negatif. Banyak sekali tulisan atau wawancara yang menyalahkan pendapat JK itu dan intinya, demokrasi berjalan seiring dengan kesejahteraan. Hanya tulisan Amich Alhumami, “Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan” (Kompas, 27/12/2007), yang memahami pernyataan JK.
Dikutipnya pendapat Lee Kuan Yew (LKY): “I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development.” Kita bisa menolak pendapat LKY, tetapi ternyata apa yang dikatakannya itu memang sesuai dengan kondisi rakyat Singapura dan betul-betul mampu mewujudkan kesejahteraan.
Demokrasi uang
Demokrasi liberal umumnya digambarkan sebagai demokrasi terbaik yang pernah diterapkan di Indonesia. Tetapi, sebenarnya era saat itu tidaklah sebagus yang digambarkan. Silih berganti kabinet berdiri dan sekitar setahun kemudian harus bubar. Stabilitas politik tidak ada sehingga tidak memungkinkan berjalannya program yang sinambung. Bung Hatta dalam pidato perpisahannya saat akan mengundurkan diri (1956) mengecam perilaku partai-partai yang didasarkan atas kepentingan pribadi yang sempit. Gemas terhadap jatuh-bangunnya kabinet, Bung Karno menunjuk Juanda (tokoh nonpartai) sebagai PM pada April 1957, yang merupakan awal dari Demokrasi Terpimpin.
Dalam era Demokrasi Terpimpin, banyak tokoh yang berjasa besar pada bangsa ditangkap dan ditahan sampai akhir 1965, antara lain Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Hamka, Mochtar Lubis, dan Imron Rosyadi. Ketua MPR, ketua DPR, dan ketua MA dimasukkan ke dalam kabinet, yang bertentangan dengan prinsip checks and balances. Era Demokrasi Terpimpin sebenarnya adalah rezim otoriter.
Era Demokrasi Pancasila tak banyak berbeda. Banyak tokoh mahasiswa yang ditangkap, seperti Syahrir, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Marsillam, Mahbub Djunaedi, Hariman Siregar, dan Fadjroel Rachman. Tindakan kekerasan yang dapat dianggap melanggar HAM berat terjadi terutama di Aceh dan Irian Jaya. Peristiwa penculikan tahun 1997, kerusuhan di banyak tempat yang kuat diduga sebagai rekayasa pemerintah, kasus 27 Juli 1997, dan kerusuhan Mei 1998 adalah sejumlah contoh dari betapa rawannya situasi politik dalam rezim otoriter Orde Baru.
Dalam pidato pengukuhan guru besar di UGM, Riswandha Imawan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mulai bergerak menjauh dari pengabdian kepada kepentingan rakyat. Demokrasi telah menjadi kendaraan efektif bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan, bukan lagi diikhtiarkan untuk rakyat. Kalaupun ada konsep ikhtiar untuk rakyat, semua hanya lips service. Para pedagang tradisional yang tergusur dan korban Lapindo merasa bahwa partai dan tokoh politik tidak memerhatikan mereka.
Fakta menunjukkan bahwa biaya pemilu, pilkada, dan pilpres amat besar. Biaya dan mutu demokrasi yang dihasilkan tidak seimbang. Reaksi yang muncul, ada yang mengatakan bahwa demokrasi dapat dinomorduakan, yang penting kesejahteraan. Reaksi lain, gubernur sebaiknya ditunjuk oleh presiden.
Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik harus berjalan bersama. Jika perekonomian hanya memberi kesempatan berkembang kepada kelompok tertentu yang jumlahnya sedikit dan mengabaikan nasib sebagian besar rakyat (contohnya pembangunan pasar di banyak kota, seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Blok M, pemberian HPH kepada sejumlah kroni), demokrasi tidak akan berumur panjang. Kalaupun ada, prosesnya masih demokratis tetapi sebenarnya tidak, prosedural tetapi tidak substansial.
Suara rakyat dapat dibeli sebagaimana kita lihat contohnya dalam pemilu dan pilkada di banyak tempat. Maka, yang muncul sebagai calon dalam pilkada dan pilpres adalah mereka yang punya uang dalam jumlah amat besar, walaupun mereka tidak punya integritas. Tokoh yang punya kemampuan dan karakternya baik tak bisa muncul karena tidak punya uang. Maka, demokrasi kita adalah demokrasi uang.
Tercampaknya rasa keadilan
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keberanian lembaga-lembaga hukum. Pemerintah yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari konsep dasar hak asasi dan kesetaraan individu yang dijunjung tinggi. Lumpuhnya demokrasi pada 1957-1965 tidak bisa dilepaskan dari lumpuhnya rule of law dan lembaga-lembaga hukum.
Pada 1950-an, menurut Daniel S Lev, dunia hukum Indonesia masih punya integritas. Jaksa sangat kukuh dan tidak memberi ruang untuk kompromi. Ketua MA punya wibawa tinggi dan menempatkan diri sejajar dengan presiden. Lembaga MA mulai hancur saat Bung Karno mengangkat Ketua MA Wiryono Prodjodikoro sebagai Menteri Penasihat Hukum.
Pada era Orde Baru, kondisi lembaga hukum secara struktural ditempatkan posisinya sesuai UU, tetapi secara umum tidak diisi oleh pribadi-pribadi yang punya keberanian. Wakil Jaksa Agung Priatna Abdur Rasyid, yang berani menentang perintah Pak Harto untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Dirut Pertamina, diberhentikan. Kepala Polri Hugeng yang ke rumah Pak Harto di Jalan Cendana untuk melaporkan rencana menindak pengusaha backing penyelundup ternyata berjumpa sang pengusaha itu di sana.
Lembaga hukum saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun sudah ada kemajuan. Banyak keputusan hakim yang dianggap masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan, seperti yang terkait pembalakan liar. Ketidaksediaan MA diperiksa oleh BPK dan adanya rekening liar MA membawa citra kurang baik. Komisi Yudisial yang tugasnya mengawasi para hakim justru seorang anggotanya tersangkut kasus.
Seorang guru besar ilmu hukum menulis bahwa teori tentang hukum sebagai peranti rekayasa pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering) di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (law as a tool of corruption engineering). Itu adalah salah satu kesimpulan dari forum Experts Meeting saat membedah PP No 37/2006 di Pusat Studi Antikorupsi FH UGM. Menurut dia, paham natural law yang menekankan bahwa hukum harus berdasar moral, memuat budi baik, dan penuh rasa keadilan telah tercampak dari proses pembuatan hukum dan digantikan oleh aliran positivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah apa pun yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membuatnya.
Kenyataan pahit
Amich Alhumami menyimpulkan bahwa hubungan demokrasi-kesejahteraan tidak bersifat linier-kausalistik, melainkan nonlinier-kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik.
Sejumlah catatan di atas membenarkan kesimpulan Amich Alhumami itu. Kita masih perlu banyak belajar dan memperbaiki banyak hal untuk bisa mewujudkan demokrasi. Kalau harus menjawab mana yang dipilih kalau kita harus memilih demokrasi atau kesejahteraan, JK mengikuti LKY dan memilih kesejahteraan. Banyak tokoh lain tetap bersikeras bahwa kita tidak harus memilih, kita bisa memperoleh keduanya.
Sayang kenyataan pahit menunjukkan bahwa kita justru tidak memperoleh keduanya. Kita tidak memperoleh demokrasi dan kita tidak memperoleh kesejahteraan. Tetapi, kita tidak mungkin kembali kepada otoritarianisme karena sejarah menunjukkan bahwa sistem itu tidak mampu memberi kesejahteraan. Jadi, kita harus terus memperjuangkan demokrasi dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu penegakan hukum dan keadilan secara nyata dan memperbaiki kehidupan kepartaian dengan menampilkan politisi yang berkarakter, berbudaya, bertanggung jawab, dan punya rasa malu.
Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng
Disalin sesuai naskah sumbernya:
Kompas, Kamis, 03 Januari 2008
Klik di sini untuk membaca naskah aslinya
Demokrasi Tanpa Integritas Moral
Triyono Lukmantoro
Demokrasi memang menjengkelkan. Cara yang harus ditempuh memusingkan, hasil yang diraih jarang memuaskan. Demokrasi tidak memberi kesejahteraan, tetapi justru melahirkan pertikaian dan pemiskinan. Rakyat yang seharusnya diposisikan sebagai penguasa tertinggi dalam arena perpolitikan, ironisnya, dijerumuskan dalam keterasingan.
Intinya, demokrasi hanya melahirkan absurditas, keadaan yang tidak bisa dimengerti dengan kejernihan nurani atau akal waras. Keadaan itulah yang menjadikan demokrasi gampang mendatangkan banyak kekecewaan. Kondisi buruk yang diembuskan demokrasi diperparah elite politik dan aparat penegak hukum yang menunjukkan aksi-aksi keblunderan. Simak misalnya, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pengulangan pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone, Gowa, Tana Toraja, dan Bantaeng. Bukankah ini menjadikan ketidakpastian berakumulasi?
Banyak perilaku wakil rakyat tidak mencerminkan aspirasi pemilihnya. Bahkan, opini publik sengaja disingkirkan guna mencapai aneka kepentingan sesaat. Bagaimana mungkin wakil rakyat memilih seseorang yang kredibilitasnya diragukan untuk memimpin komisi yang berperan melibas korupsi? Itu hanya sebuah contoh nyata tentang betapa demokrasi amat mencederai perasaan rakyat. Kasus-kasus pencederaan nurani sejenis itu mudah ditampilkan sehingga membentuk statistik politik yang mengundang kegeraman.
Bukan kebetulan jika Wapres Jusuf Kalla yang juga ketua partai besar berujar, demokrasi cuma cara, alat, atau proses, dan bukan tujuan. Demokrasi boleh dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Inikah tanda-tanda zaman tentang kejenuhan dan kemuakan terhadap demokrasi? Jika elite politik diselimuti gejala kemualan terhadap demokrasi, bagaimana dengan rakyat yang telanjur percaya pada janji-janji manis demokrasi?
Kritik Plato
Bagaimana kita bisa keluar dari labirin demokrasi? Salah satu jawaban yang dapat dikedepankan adalah jika kita bisa membaca dengan baik pengkritik demokrasi. Kecaman atas pelaksanaan demokrasi bukan fenomena yang sama sekali baru. Filsuf Plato (428-348 SM) mengingatkan, demokrasi merupakan kekuasaan yang menunjukkan kemerosotan jiwa. Plato memberi resep, negara seharusnya dikendalikan filosof-raja. Perpaduan kedua sosok itu niscaya akan menyembuhkan berbagai bobrok demokrasi, dan otomatis negara dipimpin oleh pencinta kebijaksanaan yang mengetahui hakikat kebenaran dan keadilan. Dan sosok ini mampu menerapkan aneka gagasan itu dalam praktik perpolitikan.
Seperti diuraikan Mark Moss (A Critical Account of Plato: a Critique of Democracy), Plato mengecam demokrasi karena tiga alasan. Pertama, demokrasi mengarah pada “aturan gerombolan” yang dengan kekuasaannya menjadi kaki tangan “pencari kenikmatan” yang tujuan utamanya kepuasan dari hasrat yang sesaat. Kedua, demokrasi mengarah pada aturan yang dikendalikan kaum pandir yang memiliki keterampilan retorika, namun tidak memiliki pengetahuan yang benar. Ketiga, demokrasi mengarah pada ketidaksepakatan dan pertikaian yang secara intrinsik buruk dan harus dihindarkan.
Kritik Plato atas demokrasi memang meyakinkan, dan persis seperti yang kita alami. Solusi yang ditawarkan Plato sekilas menjanjikan. Tetapi, siapa yang kini pantas dianggap figur manifestasi perpaduan filosof-raja? Jika dibaca dalam perspektif berkebalikan, kritik Plato dapat digunakan untuk memperbaiki demokrasi. Sistem perwakilan yang didominasi partai politik amat rentan melahirkan kekuasaan kaum gerombolan. Ini menunjukkan, seleksi dan pengawasan yang ketat harus diaplikasikan untuk memilih elite politik berkredibilitas tinggi.
Masalah moralitas Kelihaian elite politik dalam bersilat lidah harus dipatahkan. Mekanisme yang dapat dijalankan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kemampuan elite politik dalam berkomunikasi. Sebab, demokrasi berproses dalam diskursus. Tetapi, diskursus dalam demokrasi tidak identik adu mulut penuh kekosongan.
Diskursus yang berlangsung dengan pemakaian bahasa itu, seperti ditegaskan Jurgen Habermas (dalam Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, 2000: 221-222), harus memuat empat klaim, yakni kejelasan, kebenaran, kejujuran, dan ketepatan. Jika salah satu klaim tidak terpenuhi, proses yang terjadi bukanlah komunikasi, tetapi manipulasi.
Demokrasi memang tidak setara dengan pertikaian tanpa ujung. Untuk meraih pengambilan keputusan dalam demokrasi, lazim dijalankan dengan mekanisme suara terbanyak. Namun, prosedur ini amat rentan menghasilkan permufakatan jahat. Bukankah suara terbesar belum tentu menjadi cermin kebaikan?
Cara terbaik lain yang dapat ditempuh adalah konsensus. Pada domain ini, rasionalitas tujuan yang hanya mengatasnamakan rakyat dan menjadikannya alat untuk bertikai wajib dihilangkan. Rasionalitas komunikatif harus dikerahkan guna mencegah distorsi politik dengan kesengajaan. Artinya, demokrasi mewajibkan praktik deliberasi, yakni keterlibatan dan kemampuan rakyat dalam mengawasi setiap pengambilan keputusan.
Akhirnya, demokrasi bermuara pada masalah moralitas. Kemerosotan demokrasi lebih banyak disebabkan oleh elite politik yang tidak memiliki integritas moral. Integritas moral bukan sekadar bermakna kehidupan pribadi elite politik telah berkesesuaian dengan persetujuan publik. Integritas moral, ungkap Matthew Collins (dalam Integrity, Sincerity, and the Truth, 2003), berarti terciptanya kesatuan antara nurani yang secara internal terdapat pada manusia, perilaku eksternal yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan pada hukum moral.
Integritas moral pada demokrasi adalah keutuhan perasaan, pikiran, dan tindakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pelanggaran integritas moral adalah pengkhianatan demokrasi. Jangan berharap pada demokrasi jika elite politik tidak mengenal integritas moral!
Triyono Lukmantoro Dosen Etika Profesi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
Disalin sesuai naskah sumbernya: Kompas, Jumat, 11 Januari 2008
Klik di sini untuk membaca naskah aslinya
Reformat huruf menjadi miring dan tebal oleh staf swadayaMANDIRI
Tang & Yung (2006) melakukan penelitian mengenai kaitan demokrasi dan kinerja ekonomi di negara-negara kategori high performance Asian economies (HPAEs), menggunakan time-series technique yang disebut autoregressive distributive lag, juga menemukan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional. Kinerja ekonomi bagus tidak bergantung pada pilihan sistem politik, demokrasi, atau otoriter.
Penelitian Tang & Yung menarik untuk dilanjutkan. Mungkin disamping melihat korelasi Indeks ekonomi dan Indeks demokrasi (sistem politik) dapat juga diteliti lebih jauh tentang pengambilan keputusan. Sebab jika disimak pada negara ekonomi maju dengan sistem politik yang relative dikatakan demokratik (pada state level). Ternyata pada firms level ditunjang oleh pengambilan keputusan yang tidak demokratik (elitis, jika menggunakan terms Dahl, demokratis = non-elitis).
Dapakah ?, jika instrument sistem politik yang digunakan oleh Tang & Yung pada unit analisys “State Level”. Diterapakan pada unit analisys yang berbeda, misalkan pada “firms level” di negara-negara demokrasi.
Kedua, dapatkah ?, diteliti tentang pengambilan keputusan untuk kasus seperti penelitian Tang tersebut dengan menagbil lokus penelitian di Daerah Bali dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang relatif baik.
Pada hakekatnya pengambilan keputusan berperan sentral dibalik berbagai phenomena, baik politik, ekonomi, budaya, sosial, dsbg.
Secara umum:
Pengambilan keputusan dapat dikategorikan menjadi:
1. Pengambilan keputusan moral, jika keputusan yang diambil bermanfaat bagi pihak lain.
2. Pengambilan keputusan non-moral, jika keputusan diperuntukan bagi kepentingan diri.
3. Pengambilan keputusan a-moral, jika keputusan merugikan pihak lain.
Kategori pengambilan keputusan tersebut dapat telusuri menurut motivenya:
1. Pengambilan keputusan bermotif menjalankan kewajiban (for the shake of duty).
2. Pengambilan keputusan bermotif keuntungan (kalkulasi rasional/cost-benefit).
3. Pengambilan keputusan bermotive panggilan (inner voice).
Mengambil keputusan cenderung variatif.
1. Pertama logika (dry rasional) cenderung digunakan dalam pengambilan keputusan bermotive keuntungan.
2. Kemudian, kedua untuk pengambilan keputusan bermotive kewajiban, tools yang berkerja adalah: emosi. Terutama dalam hal membangun “kekhawtiran/khauf”. Reward dan punishment menjadi factor penggerak dari bekerjanya pengambilan keputusan bermotive kewajiban ini.
3. Berikut, adalah pengambilan keputusan bermotive panggilan (inner voice), alat yang bekerja disini adalah intuisi.
Dalam beberapa literature teology dikemukakan bahwa bekerjanya intuisi ini diawali gerakan yang berkerja di dalam hati yang dikenal dengan “Hub” dalam Islam atau “Kasih” dalam Kristen, atau “Dharma” dalam Hindu dan Budha.
Lokus penelitian Bali menarik untuk diteliti dengan serentetan pertanyaan spontan, seperti: Bagaimana nasib pranata sosial yang berdasarkan dharma dengan banjar-banjarnya, ketika harus berhadapan dengan pemilihan umum daerah. Masyarakat brahmana karena sedikit jumlahnya berhadapan dengan masyarakat waisya dan sudra yang banyak jumlahnya dan akan menjadi majority di perwakilan. Bagaiman konsep kepemimpinan adat tersebut kemudian? Juga dengan firm-firm level penunjang kemajuan ekonomi bali yang terbangun berdasarkan dharma?
Sangat menarik komentarnya. Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya.
Aturan main sangat berpengaruh pada perilaku para pemain. Pemain sepak bola tidak akan ingin memegang bola karena aturan mainnya bukanlah aturan main Volley Ball. Begitu juga sebaliknya.
Pranata sosial yang berdasarkan dharma di Bali juga termasuk dalam kelompok ATURAN MAIN. Barangkali ia bisa disebut sebagai Aturan Main tak tertulis. Mengapa memakai frasa “barangkali”? Maaf, kami juga masih belum memiliki data yang tepat terkait sifat dari Pranata sosial yang ada di Bali tersebut. Bila berkenan, sudilah kiranya untuk berbagi. Makasih sebelumnya
Dalam sebuah negara atau bahkan kelompok sosial masyarakat yang kecil, pengambilan keputusan adalah sesuatu yang vital. Kami juga sangat tertarik untuk terhadap proses pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan yang saat ini sedang kami gali adalah:
Menurut kami, ini pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Paling tidak untuk latihan merenung. 😉